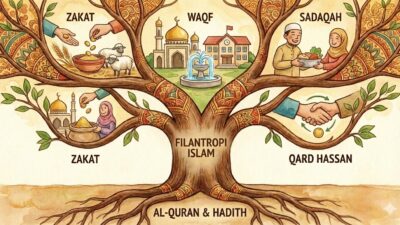SALURANSATU.COM – Opini – Tanggal 8 November 2025 Kapolri menyebut peledakan di SMAN 72 berlatar perundungan. Dua hari kemudian pengamat terorisme, Ridlwan Habib, menganalisis bahwa anak berhadapan dengan hukum (ABH, pelaku) dimaksud terendus masuk ke dalam grup media sosial terkait ideologi jahat. Lantas, 12 November, giliran Diyah Puspitarini (Komisioner KPAI) mendeskripsikan ABH tersebut sebagai anak dengan pengasuhan yang tidak adekuat.
Jika dirangkum, ketiga tokoh tersebut telah memberikan status korban ke si ABH. Rinciannya, dia adalah korban kekerasan, korban jaringan terorisme, serta korban penelantaran dan perlakuan salah.
Persoalannya, sadarkah publik bahwa penyematan status korban itu memiliki tiga implikasi?
Pertama, karena si ABH berstatus sebagai pelaku sekaligus korban, negara terlebih dulu harus mengedepankan penanganan anak itu selaku korban. Artinya, upaya pemenuhan hak-haknya selaku korban mesti didahulukan sebelum meminta pertanggungjawabannya secara pidana.
Kedua, status sebagai korban–apalagi tiga ragam korban!–selayaknya dipertimbangkan sebagai hal yang meringankan hukuman. Hakim yang nantinya menyidangkan si ABH hendaknya tidak menihilkan kondisi korban tersebut. Dari yang sudah-sudah, hakim bisa saja tutup mata terhadap realitas bahwa anak yang duduk di kursi terdakwa sesunguhnya telah bertahun-tahun menjadi sasaran serbaneka perlakuan yang tidak baik (termasuk perundungan). Alasan tipikal hakim: si ABH belum pernah diproses hukum dalam kedudukannya sebagai korban, tidak ada pemeriksaan medis dan psikologis untuk memvalidasi klaim korban, serta tidak ada saksi di persidangan yang menyebut si ABH sesungguhnya adalah korban.
Ketiga, coba baca UU Perlindungan Anak. Korban kekerasan (bersinonim dengan perundungan), korban jaringan terorisme, serta korban penelantaran dan perlakuan salah memperoleh perlindungan khusus. Bukan perlindungan biasa, melainkan perlindungan khusus. Dan setiap jenis korban memiliki bentuk perlindungan khususnya masing-masing.
Perlindungan khusus itu merupakan kewajiban sekaligus tanggung jawab pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan lembaga negara lainnya. Diberikan selekasnya, tanpa menunggu adanya putusan hakim.
Tiga implikasi di atas boleh jadi berseberangan dengan mood khalayak saat ini. Pasca ledakan, masyarakat takut, sedih, atau bahkan marah. Tapi apa boleh buat; UU Sistem Peradilan Pidana Anak mewanti-wanti siapa pun untuk membersihkan hati dari perasaan-perasaan negatif ketika berhadapan dengan ABH.
Sama halnya, UU juga mengingatkan semua pihak agar tetap memandang ABH sebagai insan yang mempunyai masa depan. Tugas kita adalah membersamai si ABH menuju masa depannya itu.
Silakan tanya murid-murid yang terkena ledakan dan keluarga mereka. Lapang dadakah mereka semua menyaksikan si pelaku peledakan mendapat tiga ‘layanan’ di atas? Satu orangtua yang saya tanya, menjawab tegas, “Tidak!”
Pelik, ya.
Reza Indragiri Amriel
Konsultan, Yayasan Lentera Anak